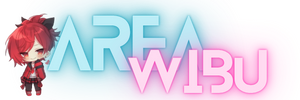Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Hujan deras mengguyur kota, dan aku terjebak di sebuah kafe kecil di sudut Shibuya. Dengan secangkir kopi hitam yang mengepul, aku membuka halaman pertama “Ningen Shikkaku” karya Osamu Dazai. “Manusia Gagal,” atau “Gagal Menjadi Manusia” begitu kira-kira kalimat pembuka yang membekas di benakku. Dan sejak saat itu, aku merasa seperti bertemu dengan refleksi dari bagian tergelap diriku sendiri yang selama ini berusaha keras kusembunyikan.
Osamu Dazai, melalui karakternya Yozo Oba, telah menguak lapisan-lapisan paling kelam dari eksistensi manusia—alienasi, ketidakmampuan untuk terhubung, kepura-puraan, dan keputusasaan yang begitu dalam hingga membuatnya merasa “gagal menjadi manusia“. Ningen Shikkaku, yang secara literal berarti “Diskualifikasi sebagai Manusia” atau “No Longer Human” dalam terjemahan Inggrisnya, bukanlah buku yang akan memberimu penghiburan atau jawaban—ia justru melemparkanmu ke jurang pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mungkin selama ini kau hindari.
Dalam esai panjang ini, aku ingin membedah novel gelap ini—bukan hanya sebagai karya sastra, tapi sebagai cermin yang memantulkan sisi tergelap dari kemanusiaan kita. Bagaimana seorang pria muda yang cerdas bisa merasa begitu terasing dari dunia manusia hingga ia merasa seperti alien yang terus-menerus berpura-pura menjadi manusia? Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana perasaan alienasi itu pada akhirnya bisa begitu relatable bahkan di era digital 2025 ini?
Kegelapan yang Memanggil: Sinopsis dan Konteks
“Ningen Shikkaku” diterbitkan pada 1948, tak lama sebelum Dazai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri bersama kekasihnya. Novel ini tersusun dalam bentuk tiga catatan pribadi milik Yozo Oba, dengan pengantar dan epilog yang dinarasikan oleh seorang pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya. Melalui catatan-catatan ini, kita menyaksikan perjalanan Yozo dari masa kecilnya yang penuh dengan kepura-puraan, masa mudanya yang dipenuhi pelarian diri melalui alkohol, obat-obatan, dan perempuan, hingga akhirnya jatuh ke dalam kegelapan total.
Sejak kecil, Yozo merasa ada sesuatu yang “salah” dengan dirinya. Ia tidak bisa memahami cara manusia berinteraksi dan emosi yang mereka ekspresikan. Untuk bertahan hidup dalam dunia yang tidak ia pahami, Yozo mengembangkan persona badut—selalu bercanda, menghibur, dan menyenangkan orang lain. “Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku adalah dengan berpura-pura menjadi badut,” tulisnya.
Namun di balik topeng itu, Yozo hidup dalam ketakutan konstan. Takut terbongkar sebagai “bukan manusia”, takut tidak bisa memahami dunia manusia, takut pada “manusia pemberani” yang ia anggap bisa menghancurkannya kapan saja. Ketakutan ini mendorongnya pada pelarian melalui alkohol, narkoba, dan seks—pelarian yang justru semakin menjauhkannya dari kemanusiaan yang ia coba raih.
Yang membuat “Ningen Shikkaku” begitu menghantui adalah fakta bahwa novel ini semi-autobiografi dari Dazai sendiri. Banyak pengalaman Yozo—termasuk percobaan bunuh diri, alkoholisme, dan perasaan alienasi yang mendalam—adalah cerminan dari kehidupan nyata Dazai. Mungkin inilah yang membuat narasi dalam novel ini terasa begitu raw dan authentic—karena ini memang suara dari jiwa yang benar-benar terpisah dari dunia.
Dualitas Manusia dalam Pandangan Dazai
“Bisakah kau membedakan mana setan dan mana manusia hanya dengan melihat wajahnya?” Pertanyaan ini muncul secara implisit di sepanjang novel Dazai. Dalam pandangan Yozo, dunia manusia terbagi menjadi dua: “manusia” sungguhan yang dia takuti dan tidak pahami, dan “setan-setan menyamar” seperti dirinya yang terus berpura-pura untuk bertahan hidup.
Namun apa yang menurut Yozo adalah dikotomi antara manusia dan “bukan manusia”, sebenarnya adalah refleksi dari dualitas yang ada dalam diri setiap manusia. Dazai, dengan kejeniusannya, menunjukkan bahwa setiap dari kita memiliki dua sisi—sisi terang yang kita tunjukkan ke dunia (angel) dan sisi gelap yang kita sembunyikan (demon).
“Semua manusia hidup dibungkus oleh kebohongan,” tulis Dazai melalui Yozo. Ini mengingatkanku pada konsep “persona” dari Carl Jung—topeng sosial yang kita kenakan untuk berinteraksi dengan dunia. Yang membuat Yozo berbeda adalah kesadarannya yang akut tentang topeng ini, dan ketidakmampuannya untuk menemukan identitas sejati di balik topeng tersebut.
Dalam satu bagian yang menghantui, Yozo mengakui bahwa ia bahkan tidak tahu bagaimana cara “menjadi dirinya sendiri”:
“Aku bahkan tidak tahu apakah aku punya ‘diri’ yang sejati. Sepanjang hidupku, aku hanya menjadi apa yang orang lain inginkan dariku. Aku adalah badut untuk teman-temanku, anak penurut untuk orang tuaku, pria romantis untuk para wanita… Tapi siapa aku sebenarnya? Apakah ada ‘Yozo’ yang asli di balik semua topeng ini?”
Ini adalah pertanyaan yang masih relevan—bahkan mungkin semakin relevan—di era digital kita. Di dunia yang dipenuhi dengan social media personas, filter Instagram, dan kehidupan yang dikurasi, berapa banyak dari kita yang benar-benar menunjukkan “diri sejati” kita? Berapa banyak yang telah menjadi begitu mahir dalam mengenakan berbagai topeng digital hingga lupa seperti apa wajah asli kita?
Kepura-puraan dan Autentisitas
Dalam salah satu bagian paling menyayat hati dari novel ini, Yozo mengakui: “Sejak pertama kali aku menyadari bahwa aku berbeda dari orang lain, aku mulai berpura-pura. Aku mencoba meniru tawa mereka, mengikuti gerakan mereka, mengulangi kata-kata mereka. Aku adalah aktor yang tidak pernah turun dari panggung.”
Kepura-puraan ini adalah strategi bertahan hidup Yozo di dunia yang tidak ia pahami. Namun ironisnya, semakin ia mencoba “menjadi manusia” melalui imitasi, semakin jauh ia merasa dari kemanusiaan itu sendiri. Ini adalah paradoks yang menyakitkan: usahanya untuk terhubung justru memperdalam alienasi yang ia rasakan.
Aku tidak bisa tidak memikirkan bagaimana paradoks ini juga hadir dalam masyarakat kita hari ini. Kita hidup di era di mana “authenticity” menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Influencer menjual “kehidupan autentik” mereka yang telah dikurasi dengan hati-hati. Perusahaan berlomba-lomba membangun “brand authenticity”. Tapi di tengah semua kebisingan tentang menjadi “autentik” ini, berapa banyak dari kita yang benar-benar berani menunjukkan bagian-bagian dari diri kita yang berantakan, gelap, atau tidak sempurna?
Yozo bukanlah karakter yang bisa kita kagumi, tapi ia adalah karakter yang bisa kita pahami. Keputusasaannya, kepura-puraannya, pelariannya—semua itu adalah ekstrem dari apa yang kita semua lakukan dalam skala yang lebih kecil. Kita semua, pada level tertentu, memakai topeng dalam interaksi sosial kita. Pertanyaannya adalah: sampai sejauh mana kepura-puraan ini sebelum kita kehilangan pegangan pada siapa diri kita sebenarnya?
Lubang Hitam Bunuh Diri
“Bunuh diri butuh keberanian.” Kalimat ini diucapkan oleh Yozo setelah percobaan bunuh dirinya yang gagal. Ada obsesi aneh dengan kematian dan bunuh diri yang menjalar di sepanjang karya Dazai, sesuatu yang tragisnya termanifestasi dalam kehidupan nyatanya juga.
Dalam “Ningen Shikkaku”, Yozo melakukan beberapa percobaan bunuh diri. Yang paling terkenal adalah episode di mana ia mencoba bunuh diri bersama seorang wanita bernama Tsuneko, yang berakhir dengan kematian wanita itu sementara Yozo selamat. Episode ini mirip dengan percobaan bunuh diri Dazai sendiri pada 1930 bersama seorang waitress bernama Shimeko Tanabe, yang juga berakhir dengan kematian perempuan tersebut.
Apa yang membuat obsesi dengan kematian ini begitu menghantui adalah bagaimana ia terhubung dengan keterasingan Yozo. Baginya, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, melainkan jalan keluar yang mungkin dari dunia manusia yang tak bisa ia pahami. “Aku tidak takut mati,” tulisnya. “Yang aku takutkan adalah hidup sebagai sesuatu yang bukan manusia.”
Ada dualitas mengerikan di sini: di satu sisi, Yozo terobsesi untuk “menjadi manusia” dan diterima; di sisi lain, ia juga menganggap kematian sebagai pembebasan dari beban untuk terus berpura-pura menjadi manusia.
Aku berpikir tentang bagaimana tema ini beresonansi di era kita yang dipenuhi dengan krisis kesehatan mental. Bunuh diri tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian di kalangan anak muda di seluruh dunia. Mungkinkah ada gema dari perasaan Yozo dalam diri mereka—perasaan terasing, tidak dipahami, dan terjebak dalam kepura-puraan yang melelahkan?
Perempuan sebagai Penyelamat dan Penghancur
Hubungan Yozo dengan perempuan adalah salah satu elemen paling kompleks dalam novel ini. Di satu sisi, perempuan-perempuan dalam hidupnya—terutama Shizuko, Yoshiko, dan istrinya—seringkali menjadi penyelamat sementara dari rasa alienasi yang ia rasakan. Di sisi lain, hubungan-hubungan ini hampir selalu berakhir dengan pengkhianatan, penyalahgunaan, atau abandonment.
“Aku tidak bisa mencintai atau dicintai,” Yozo mengakui. Baginya, perempuan adalah enigma—lebih sulit dipahami bahkan dibandingkan laki-laki. Ia mendekati mereka dengan campuran rasa takut, kagum, dan kebingungan. Namun yang paling menyedihkan adalah bagaimana ia melihat dirinya tidak layak dicintai—sesuatu yang secara tragis ia buktikan dengan memperlakukan buruk perempuan-perempuan yang mencintainya.
Dinamika ini mengingatkanku pada tokoh femme fatale dalam karya noir Edogawa Rampo. Ada elemen yang sama dalam bagaimana perempuan dipandang sebagai sesuatu yang misterius, berbahaya, sekaligus menggoda. Namun jika dalam karya Rampo perempuan sering digambarkan sebagai penggoda yang berbahaya, dalam “Ningen Shikkaku” Dazai justru menggambarkan Yozo sendiri sebagai ancaman bagi perempuan-perempuan dalam hidupnya.
Salah satu momen paling menyedihkan adalah ketika Yoshiko, yang dengan tulus mencintai Yozo meskipun mengetahui kerusakannya, akhirnya dikhianati dan ditinggalkan. “Aku mencintainya,” akui Yozo, “tapi aku tidak tahu bagaimana cara mencintai tanpa menghancurkan.”
Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang hubungan interpersonal di era modern kita. Di dunia di mana dating apps membuat koneksi romantis menjadi sesuatu yang seolah bisa dibuang begitu saja (swipe left), berapa banyak dari kita yang, seperti Yozo, tidak tahu bagaimana cara membangun hubungan yang dalam dan bermakna? Berapa banyak yang, seperti Yozo, merasa tidak layak untuk dicintai?
Obat-obatan, Alkohol, dan Pelarian Diri
“Sejak pertama kali aku minum alkohol, aku menyadari bahwa inilah obat yang tepat untuk kondisiku.” Bagi Yozo, alkohol dan kemudian morfin bukanlah sekadar kesenangan—mereka adalah alat untuk melarikan diri dari beban menjadi “manusia”.
Pelarian melalui zat-zat ini digambarkan dengan detail yang menyakitkan oleh Dazai. Yozo menggambarkan bagaimana alkohol membuatnya bisa tertawa dengan tulus untuk pertama kalinya. Bagaimana morfin memberikan kebahagiaan palsu yang tidak pernah bisa ia temukan dalam interaksi manusia. Dan bagaimana, pada akhirnya, ketergantungan pada zat-zat ini semakin mengisolasinya dari dunia manusia.
Apa yang membuat narasi Dazai tentang kecanduan begitu kuat adalah kejujurannya yang brutal. Ia tidak mengglamourkan obat-obatan ini, juga tidak sekadar menghakiminya. Ia menunjukkan keduanya—kelegaan sementara yang mereka berikan dan kehancuran jangka panjang yang mereka sebabkan.
Aku berpikir tentang bagaimana tema ini tetap relevan di era kita. “Opioid crisis” di Amerika. Tingginya tingkat alkoholisme di kalangan profesional muda. Kecanduan media sosial dan stimulasi digital. Bukankah ini semua adalah bentuk-bentuk pelarian modern dari tekanan untuk “menjadi manusia”? Bukankah kita semua, pada level tertentu, mencari pelarian dari realitas yang kadang terasa terlalu berat untuk ditanggung?
Kesepian di Era Konektivitas
“Aku selalu sendirian, bahkan ketika dikelilingi banyak orang.” Kalimat ini mungkin adalah esensi dari alienasi yang dirasakan Yozo. Dan aku tidak bisa tidak berpikir betapa resonannya kalimat ini di era kita yang paradoksal—era di mana kita lebih terhubung secara digital namun mungkin lebih kesepian secara emosional.
Di dunia Yozo, alienasi itu berasal dari ketidakmampuan intrinsik untuk memahami manusia. Di dunia kita, alienasi itu mungkin berasal dari superfisialitas koneksi-koneksi kita. Kita memiliki ratusan “teman” di media sosial namun sedikit yang benar-benar mengenal kita. Kita terhubung 24/7 namun sering merasa tidak ada yang benar-benar “melihat” kita.
Dazai seolah telah memprediksi paradoks modern ini tujuh dekade lalu. Melalui Yozo, ia menggambarkan manusia yang terhubung secara fisik namun terasing secara emosional. Yozo selalu dikelilingi orang-orang—teman sekolah, rekan sesama seniman, pencinta, istri—namun tidak pernah benar-benar merasa terhubung dengan mereka.
“Mereka tertawa, dan aku ikut tertawa. Mereka menangis, dan aku mencoba menangis. Tapi aku selalu terlambat selangkah. Selalu ada jarak yang tidak bisa kujembatani.”
Bukankah ini menggambarkan banyak interaksi kita di era digital? Scroll through feed, double tap, drop a comment, repeat. Kita berpartisipasi dalam ritual sosial tanpa benar-benar hadir secara emosional. Kita connected tetapi tidak benar-benar connecting.
Sisi Gelap Modernitas Jepang
Untuk sepenuhnya memahami “Ningen Shikkaku”, kita perlu memahami konteks historisnya. Novel ini ditulis dan diterbitkan segera setelah Perang Dunia II, ketika Jepang sedang mengalami transformasi dramatis dari negara imperial menjadi negara yang diduduki dan kemudian direkonstruksi di bawah pengaruh Amerika.
Yozo, meskipun permasalahan utamanya bersifat eksistensial dan personal, juga adalah produk dari zamannya. Ia tumbuh di era Taisho dan awal Showa, masa ketika Jepang sedang menjalani modernisasi dan westernisasi yang cepat. Konflik antara nilai-nilai tradisional Jepang dan pengaruh Barat menciptakan semacam krisis identitas kolektif—sesuatu yang tercermin dalam krisis identitas personal Yozo.
“Aku tidak tahu lagi nilai-nilai apa yang harus dipegang,” tulis Yozo di satu bagian. Ini adalah refleksi dari kebingungan yang dirasakan banyak orang Jepang pasca-kekalahan dalam perang. Nilai-nilai lama telah dihancurkan, yang baru belum sepenuhnya terbentuk.
Di era kita yang dipenuhi disrupsi teknologi, globalisasi, dan krisis-krisis global (dari pandemi hingga perubahan iklim), aku melihat gema dari kebingungan serupa. Banyak dari kita yang, seperti Yozo, tidak yakin nilai-nilai apa yang harus dipegang di dunia yang berubah terlalu cepat.
Seni Pelarian Ekspresi
Salah satu aspek menarik dari karakter Yozo adalah bakatnya sebagai seniman. Ia adalah ilustrator berbakat, dan untuk sementara, seni menjadi satu-satunya cara dia bisa mengekspresikan diri dengan “jujur”.
“Ketika aku menggambar, untuk sejenak aku merasa ada koneksi antara tanganku dan hatiku.” Seni, bagi Yozo, adalah momen langka di mana topeng-topengnya bisa terlepas. Di kanvas, ia bisa mengekspresikan ketakutan, kebingungan, dan kesedihannya tanpa perlu berpura-pura.
Namun seperti halnya aspek lain dalam hidupnya, hubungan Yozo dengan seni juga bermasalah. Ia menggunakan bakatnya untuk mendapatkan pujian dan penerimaan. Ia menjual karyanya untuk mendapatkan uang yang kemudian ia habiskan untuk alkohol dan perempuan. Bahkan aspek hidupnya yang paling “autentik” pun akhirnya terkontaminasi oleh kepura-puraan dan pelarian diri.
Aku berpikir tentang bagaimana dinamika ini tetap relevan di industri kreatif hari ini. Berapa banyak seniman yang merasa terperangkap antara ekspresi diri yang jujur dan tuntutan pasar? Berapa banyak yang, seperti Yozo, akhirnya menjual bakat mereka untuk penerimaan sosial atau keuntungan finansial, dengan mengorbankan integritas artistik mereka?
Nihilisme dan Pencarian Makna
“Hidup tidak pernah memiliki makna bagiku.” Kalimat ini, yang muncul di catatan ketiga Yozo, mungkin adalah inti dari nihilisme yang disuarakan Dazai melalui karakternya. Bagi Yozo, hidup tidak memiliki tujuan intrinsik, tidak ada nilai moral absolut, tidak ada makna besar yang menanti untuk ditemukan.
Nihilisme ini memiliki kemiripan dengan pemikiran eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre atau Albert Camus, yang juga menulis pada periode pasca-Perang Dunia II. Seperti “The Stranger” karya Camus, “Ningen Shikkaku” menggambarkan individu yang terasing dari norma-norma sosial dan makna-makna konvensional.
Yang membuat nihilisme Yozo begitu menyayat hati adalah karena ia tidak menginginkannya. Ia ingin menemukan makna. Ia ingin menjadi bagian dari umat manusia. Ia ingin percaya pada sesuatu. Tetapi ia merasa tidak mampu.
“Aku melihat orang-orang pergi ke kuil, berdoa dengan khusyuk. Aku melihat mereka jatuh cinta, berkomitmen pada hubungan. Aku melihat mereka berjuang untuk cita-cita, untuk negara, untuk keluarga. Dan aku ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi aku tidak bisa.”
Di era skeptisisme dan krisis spiritualitas kita, nihilisme Yozo mungkin terasa semakin relevan. Kita hidup di dunia post-truth di mana narasi-narasi besar telah runtuh, di mana institusi-institusi tradisional (dari agama hingga pemerintah) telah kehilangan otoritas moralnya. Berapa banyak dari kita yang, seperti Yozo, ingin percaya pada sesuatu tetapi merasa tidak mampu?
Kami Tetap Ada
Jika Yozo hidup di 2025, aku membayangkan ia akan menjadi figur yang familiar namun tetap alienated. Mungkin seorang content creator yang menjual persona palsu di TikTok atau Instagram. Mungkin seorang programmer berbakat yang menghabiskan malamnya sendirian di depan layar. Mungkin seorang “doomscroller” yang menghabiskan jam-jam panjang menyerap kekacauan dunia melalui timeline media sosial.
Era digital kita menawarkan lebih banyak kesempatan untuk bersembunyi di balik topeng-topeng digital. Kita bisa menjadi siapa saja online—menjadi orang berbeda di platform berbeda. Dan dalam banyak hal, ini semakin memperdalam alienasi ala Yozo. Kita lebih terhubung namun lebih kesepian. Lebih visible namun kurang terlihat. Lebih ekspresif namun kurang dimengerti.
Jika dulu Yozo menggunakan alkohol dan morfin sebagai pelarian, hari ini ia mungkin akan menggunakan doom-scrolling, binge-watching, atau video game. Cara-cara kita untuk melarikan diri dari realitas mungkin telah berubah, tetapi dorongan untuk melarikan diri itu sendiri tetap sama.
Dan inilah yang mungkin membuat “Ningen Shikkaku” tetap menjadi novel yang powerful hingga hari ini, tujuh dekade setelah diterbitkan. Ia berbicara tentang kondisi manusia yang universal dan timeless—keterasingan, kesepian, kepura-puraan, dan pencarian akan otentisitas dan koneksi. Kondisi-kondisi yang, ironisnya, mungkin semakin diperparah oleh “kemajuan” teknologi kita.
Menerima Dualitas Kita
Jika ada pelajaran yang bisa kita petik dari kehancuran Yozo, itu adalah bahaya dari menolak dualitas kita sebagai manusia. Yozo gagal memahami bahwa kepura-puraan, pada level tertentu, adalah bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia. Bahwa kita semua memakai topeng-topeng sosial. Bahwa kita semua memiliki sisi terang dan gelap.
Daripada menerima dualitas ini, Yozo memandangnya sebagai bukti bahwa ia “bukan manusia”. Ia melihat jarak antara persona publiknya dan perasaan internalnya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang fundamentally wrong dengan dirinya.
Di sinilah mungkin letak tragedi terbesar Yozo—dan mungkin juga Dazai. Mereka tidak bisa menerima bahwa menjadi manusia berarti hidup dengan kontradiksi-kontradiksi internal. Bahwa kita semua adalah sekumpulan paradoks berjalan. Bahwa tidak ada yang sepenuhnya angel atau sepenuhnya demon—kita semua adalah campuran dari keduanya.
“Ningen Shikkaku” pada akhirnya adalah peringatan bagi kita semua—peringatan tentang bahaya dari ketidakmampuan untuk menerima kompleksitas diri kita sendiri. Dan di era yang terobsesi dengan kesempurnaan, autentisitas curated, dan personal branding, peringatan ini terasa lebih relevan dari sebelumnya.
Ketika aku menutup halaman terakhir novel Dazai itu di kafe yang sekarang mulai sepi, hujan di luar telah berhenti. Aku menatap refleksiku di jendela kafe yang berembun—separuh wajah, separuh bayangan. Mungkin itulah kita semua, pikirku. Separuh cahaya, separuh bayangan. Dan mungkin, tidak seperti Yozo, tugas kita bukanlah menghilangkan bayangan itu, melainkan menerimanya sebagai bagian tak terpisahkan dari siapa kita.
Karena pada akhirnya, menjadi manusia tidak berarti tidak memiliki sisi gelap—melainkan belajar hidup dengan sisi gelap itu tanpa membiarkannya mengambil alih sepenuhnya. Sesuatu yang, dengan tragisnya, tidak pernah dipelajari oleh Yozo Oba, protagonis yang gagal menjadi manusia namun mungkin justru menjadi cermin paling jujur tentang apa artinya menjadi manusia.